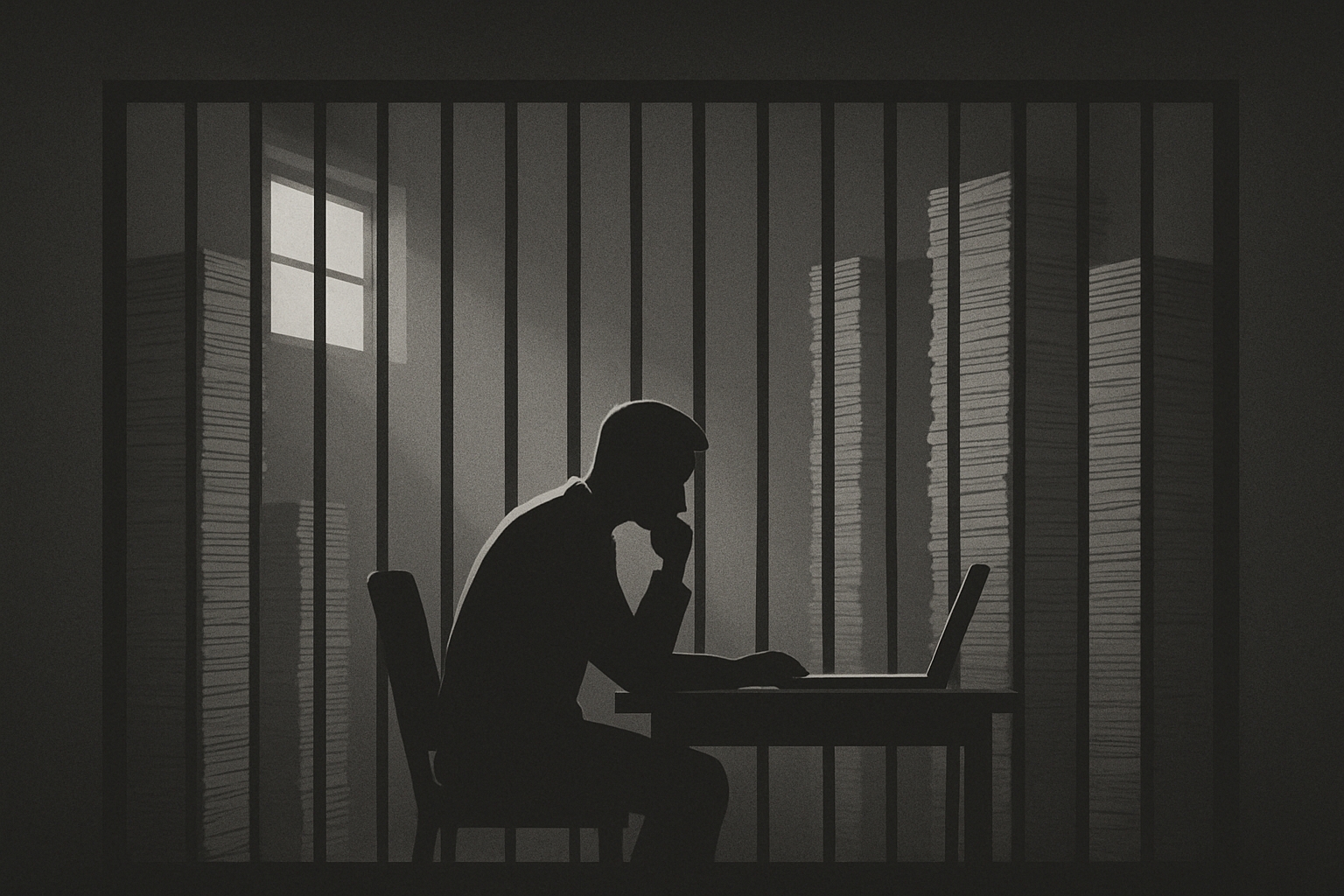Permasalahan pengungsi/pencari suaka internasional sudah menjadi suatu hal yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Terlebih setelah beberapa tahun terakhir kolom berita dipenuhi dengan pemberitaan pengungsi/pencari suaka asal Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia setelah terusir dari tempat tinggalnya di Myanmar. Selain itu, kondisi keamanan geopolitik dunia yang tidak stabil berpengaruh besar terhadap pergerakan pengungsi/pencari suaka ini. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah/tempat tinggalnya karena konflik, ancaman keamanan, persekusi, dan atau pelanggaran HAM yang mengharuskan mereka pergi mencari tempat perlindungan yang aman di negara lain.
Seringkali istilah pengungsi/pencari suaka disandingkan bersama. Keduanya memiliki latar belakang yang serupa namun masih memiliki perbedaan. Persamaannya adalah kondisi yang memaksa mereka pergi meninggalkan negara asalnya dikarenakan konflik, ancaman keamanan, persekusi dan atau pelanggaran HAM. Perbedaannya yang paling terlihat adalah status yang dipegang. Pencari suaka pada dasarnya adalah mereka yang pergi meninggalkan negara asalnya dan masih menunggu/dalam proses untuk statusnya sebagai pengungsi disetujui oleh United Nation High Commisioner for Refugee (UNHCR) selaku badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani isu pengungsi. Jadi para pencari suaka secara status hukum, perlindungan, dan haknya masih terbatas jika dibandingkan dengan mereka yang sudah disetujui dan memegang status sebagai pengungsi.
Aturan dan Posisi Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Pengungsi/Pencari Suaka
Menanggapi permasalahan pengungsi ini, negara-negara di dunia memberikan perhatian terhadap upaya penyelesaiannya. Terlebih bagi mereka yang turut menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Tapi apakah Indonesia turut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967?
Sebelum itu kita harus tahu terlebih dulu apa itu Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Bisa dibilang, Konvensi 1951 adalah produk aturan pertama yang berhasil dirancang oleh UNHCR untuk menangani isu pengungsi. Dilaksanakan pada tahun 1951 di Jenewa, konvensi lahir untuk mengatasi permasalahan para pengungsi yang berada tersebar di luar wilayah negara asalnya akibat dari Perang Dunia II, tepatnya sebelum tanggal 1 Januari 1951. Namun dikarenakan keamanan dunia yang saat itu masih belum stabil, persebaran pengungsi masih terus meningkat hingga awal tahun 1960an. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan aturan untuk mengakomodir para pengungsi yang jumlahnya terus bertambah ini. Maka dirancang dan disepakati protokol tambahan untuk melengkapi konvensi 1951, yakni protokol 1967.
Indonesia hingga saat ini masih belum turut menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Artinya Indonesia belum turut meratifikasi kedua aturan tersebut. Tetapi bukan berarti Indonesia lepas tangan terhadap penanganan permasalahan pengungsi/pencari suaka dari luar negeri. Terlebih, secara letak geografis Indonesia berada di tempat yang strategis. Menjadikannya sebagai salah satu tempat persinggahan terakhir para pengungsi/pencari suaka sebelum nantinya diberangkatkan menuju ke negara ketiga seperti Australia.
Posisi Indonesia yang tidak bisa mengelak dari kadatangan gelombang para pengungsi/pencari suaka ini juga diperkuat dengan aturan yang tercantum pada Konvensi 1951 Pasal 33 yang menerangkan bahwa “Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” Hal ini yang kemudian dikenal sebagai prinsip non-refoulment.
Walaupun mungkin Indonesia tidak terikat secara hukum internasional karena bukan termasuk bagian dari Negara Pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, akan tetapi prinsip non-refoulment ini sudah menjadi semacam customary international law atau norma umum yang yang diakui komunitas internasional. Di samping itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Aturan ini menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam penanganan isu pengungsi.
Kondisi Pengungsi di Indonesia
Mengutip dari laman resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, menurut data UNHCR sampai pada bulan September 2024 ada sekitar 11.735 pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan masih bisa terus meningkat mengingat gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang masih berdatangan di awal tahun 2025 dan kondisi keamanan dunia yang sedang tidak stabil dan dilanda perang berkepanjangan.
Status Indonesia yang masih belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ternyata memberikan beberapa kendala dalam penanganan isu pengungsi/pencari suaka dari luar negeri ini. Salah satunya adalah wewenang untuk memberikan status pengungsi. Alhasil pemerintah Indonesia harus bergantung pada UNHCR melalui prosedur penentuan Refugee Status Determination (RSD) yang ternyata waktu tunggunya juga tidak sebentar. Dampaknya adalah, pengungsi/pencari suaka dari luar negeri yang ada di Indonesia jadi menggantung nasibnya menunggu kejelasan status dan ke negara mana mereka akan ditempatkan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tidak bisa memutuskan sendiri status para pengungsi ini. Ketidakjelasan ini yang kemudian membuat para pengungsi/pencari suaka dari luar negeri menunggu hingga bertahun-tahun di Indonesia.
Selain itu, permasalahan lain pun ikut muncul. Masyarakat yang awalnya menerima kedatangan para pengungsi/pencari suaka kini mulai memberikan respon penolakan. Terutama masyarakat yang wilayahnya berulang kali menjadi tempat persinggahan para pengungsi/pencari suaka. Salah satunya yang terjadi di Pulau Weh, Aceh pada tahun 2023. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Penolakan yang terjadi dipicu oleh sikap dan perilaku para pengungsi/pencari suaka asal Rohingya itu sendiri yang dirasa tidak menghormati budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. Ditambah juga munculnya kecemburuan sosial yang mana masyarakat merasa pemerintah terlalu banyak membantu pengungsi/pencari suaka Rohingya, padahal masih banyak warga sekitar yang juga masih kesusahan dan membutuhkan bantuan.
Solusi yang Ditawarkan
Menanggapi permasalahan pengungsi/pencari suaka ini, UNHCR menawarkan tiga solusi. Yang pertama adalah penempatan ke negara ketiga (resettlement country), salah satu contohnya seperti ke Australia. Solusi kedua yang ditawarkan adalah pemulangan secara sukarela (Assisted Voluntary Return) yang tentunya hal ini bisa dilakukan jika konflik di daerah asal mereka sudah berakhir. Solusi ketiga adalah integrasi lokal di negara pemberi suaka.
Penulis juga merasa Pemerintah Indonesia masih bisa mengevaluasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah penanganan permasalahan pengungsi/pencari suaka selama ini sudah efektif atau belum. Selain itu upaya-upaya mencari solusi terbaik untuk manangani permasalahan pengungsi/pencari suaka ini juga harus terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan kerja sama lintas kementerian, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM (International Organization for Migration) serta pihak-pihak terkait lainnya agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak.
Pada akhirnya, permasalahan terkait pengungsi/pencari suaka dari luar negeri ini akan tetap ada selama manusia terus berkonflik satu sama lain dan negara tidak bisa menjamin tempat yang aman bagi masyarakatnya. Mereka (pengungsi/pencari suaka) juga sebenarnya tidak ingin meninggalkan kampung halamannya jika tidak terpaksa karena situasi dan kondisi yang ada. Pengungsi/pencari suaka yang tiba di Indonesia pun mengerti bahwa mereka tidak bisa tinggal selamanya di negara ini, akan tetapi proses menunggu kepastian status dan penempatan negara ketiga menjadi kendala bersama baik pengungsi maupun pemerintah Indonesia.
Ditulis oleh: Ahmad Soim, S.IP. (Analis Keimigrasian Ahli Pertama). Ahmad Soim adalah seorang pegawai pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini ditugaskan pada Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik (Pusdatin KP). Penulis merupakan lulusan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan memiliki ketertarikan pada isu-isu seperti perlintasan orang, migrasi, pengungsi, perbatasan negara dan keamanan.